Gurauan Kota 2
Itu
serpihan wawancara yang Yan terima Desember kala dia melamar pekerjaan di salah
satu kantor pemerintah. Yan bingung dengan kata yang dilontarkan pewawancara
itu. “Adakah yang salah jika aku tidak membawa uang? Uang pun tak tertera
sebagai syarat-syarat untuk melamar,” benak Yan berpikir, waktu itu. Kerikil-kerikil
jalanan seolah menghalangi ayunan tungkai Yan untuk kembali ke kontrakan
sederhananya. Dua minggu berlalu dari waktu wawancara kantor. Hasilnya, Yan yang
datang ke wawancara tanpa uang, tak lolos jadi pegawai kantor.
Sekarang,
berselang empat bulan dari kejadian itu, Yan kembali menghadapi wawancara. Yan tidak membawa hal lain kecuali
arsip-arsip kuliah dan seonggok dagingnya sendiri. Bernas-bernas keringat
membuah di leher coklatnya.
“Akankah
aku ditanyai tentang uang lagi?” Otak Yan kembali menggumam.
Ingatan
Yan akan kejadian itu hilang seketika tatkala seorang wanita duduk seraya
tersenyum ke Yan. Yan tak membalas senyuman manis wanita itu. Hanya terlihat
semburat urat kehijau-hijauan menghiasi kening Yan. Juga di lehernya. Berulang
kali nafas panjang terhirup dan terhembus dari tenggorokan keringnya mencari suasana
nyaman untuk menghadapi wawancara dengan wanita itu. Tanpa disuruh, tangannya
meraih pegangan kursi plastik dan merebahkan tubuh getirnya ke busa-busa kursi.
Kecemasan akan masa depan menghantui pikirannya membuat dia masih tetap
termenung memandangi jendela yang terbuka itu.
“Anda,
Janita Dwi Putra?”
“Iya..
Iya.. Iya Bu. Panggil saja Yan.” Pertanyaan itu membuyar lamunannya.
“Oke
Ian. Saudara Ian. Kenapa? Saudara terlihat sangat gugup.”
“Saya..
Gugup... Hmm. Iyaa.. Gugup.. Saya takut Bu. Saya takut... Waktu itu.. Desember 2004, saya ditolak
kerja. Saya takut itu terulang lagi.” Jawab Yan terbata-bata.
“Lalu?”
“Itu
Bu.. Miskin. Iya.. Miskin.” Jawab Yan, lalu terdiam.
“Miskin?
Maksudnya?” Ibu itu terbingung mendengar kalimat-kalimat Yan.
“Waktu
itu saya ditanyakan tentang uang. Saya tidak membawa apa-apa. Hingga ketika
pengumuman, saya ditolak. Saya tak tahu tentang itu.”
“O...
Oke. Lupakan itu. Itu cerita lain. Saya lihat, nilai-nilai Anda tidak tergolong
buruk. Sepertinya, Anda begitu sulit mencari pekerjaan. Ada masalah dengan cara
berkomunikasi?”
Impuls
syarafnya tersentak. Yan bersiap. Yan menghirup nafas dua oktaf. Panjang.
Berkali-kali. Serasa ada kekuatan dari jiwanya untuk berbicara. Berkali-kali
nafas itu. Nafas itu sedikit memakan waktu, namun ibu itu tetap bersabar
menunggu kalimat-kalimat keluar dari mulut Yan. Yan berbicara.
“Tidak
ada. Saya aktif berorganisasi ketika di kampus. Hingga akhirnya saya lulus,
lalu Saya menemukan suatu kehidupan yang jauh lebih sulit daripada perkuliahan.
Saya hanya seorang perantau dari tanah Sumatera. Tak mengerti apa-apa tentang
kota ini. Saya mencoba untuk bertahan hidup, namun ternyata itu jauh lebih
sulit dari apa yang Saya bayangkan. Aku tidak bisa memberikan apa-apa lagi
kecuali kepercayaan dari mereka yang akan memberikan saya pekerjaan. Saya hanya
ingin pulang dengan sesuatu yang dapat Saya banggakan ke orangtua. Hanya itu.
Ya. Hanya itu” Yan berusaha sesantai mungkin. Air liurnya sesekali diteguk.
Kata-kata
itu meluncur begitu saja dari mulut Yan. Kesederhanaan nampak dari wajahnya
yang lusuh. Dia tidak ingin bersandiwara dengan kalimat-kalimat yang bermaksud
memberikan janji kepada kantor itu. Lebih baik baginya untuk mengutarakan apa
yang dia alami. Ketakutan yang menghantuinya sekarang telah berubah menjadi
sebuah prinsip.
“Oh
Ya? Begini.... Ditengah persaingan global ini, kantor kami membutuhkan
orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berprinsip untuk maju. Dan kelihatannya
Anda tidak seperti yang kami inginkan. Dengan argumen Anda, Anda tidak bisa
menjamin bahwa Anda bisa memajukan kantor ini.”
Yan
terkesiap dengan jawaban sekaligus peremehan itu. Pikirannya membuncah dan dadanya
susut. Yan kembali menarik nafas. Kali ini lebih panjang dari sebelumnya. Nafas
itu membuatnya menjadi tenang. Tenang.
“Tidak
Bu. Orang yang lemah adalah orang yang hanya menuruti permintaan orang lain,
padahal bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Sepertinya, saya lebih memilih
untuk tetap dengan apa yang saya inginkan. Itu bahkan lebih tangguh daripada
orang plin-plan yang mau saja menuruti kehendak orang lain.” Yan menjawab
pertanyaan wanita itu dengan sedikit tersenyum. Raut muka wanita itu berubah, menampakkan
ketidaksukaan. Ibu itu sedikit tersinggung dengan jawaban Yan.
“Oke.
Kalau memang begitu. Anda bisa menunggu hasil wawancara ini satu minggu lagi.
Terima kasih dan silahkan.”
“Terima
kasih Bu.” Yan kembali menyunggingkan senyumannya. Kali ini justru wanita itu
yang tidak membalas senyum Yan. “Sesingkat itu?” Yan berpikir. Tatkala dia
membalikkan badannya, terlihat dari pantulan kaca pintu, pemuda yang berjas
hitam lengkap sedang memberikan amplop putih ke pewawancara. Pemuda itu dan
pria pewawancara berjabat tangan seraya mengobrol entah apa yang dikatakan.
Kali ini Yan tak terkejut dengan sesuatu yang dia lihat. Percakapannya dengan
wanita tadi membawanya ke sifat yang sesungguhnya. Dia berjalan santai ke pintu
dan berpapasan dengan pemuda berjas hitam, sang pemberi amplop.
Waktu
terus berlalu. Dan satu minggu berlalu.
Pagi
hari, tatkala jiwa Yan ingin berucap “Aku berhasil.”
Hari
ini, terhitung seminggu sejak wawancara itu. Dentingan gitar Iwan Fals dari
radio tua menemani beberapa orang di warung kopi itu, termasuk Yan yang tengah
menyeruput kopi hitam. Kopi hitam pekat yang kopi thok tanpa adonan gula serasa merangsang tubuh Yan agar jauh dari
kekantukan.
Sebuah
televisi bergaya klasik meracau di sudut warung. Kali itu, siaran televisi
mengingatkan sesuatu tentang negeri ini. Yan saat ini benar-benar berada di
kehidupan yang sesungguhnya. Jauh dari kata diskriminasi, berkumpul dengan
insan-insan yang malang, insan-insan yang berseliweran dengan kehidupan yang
jujur. Bukan dengan tikus-tikus berdasi, macam petinggi negara yang sedang
direkam di televisi itu.
“Oalah
bapak. Sekiranya wes tua, jangan
makan uang negara lagi. Piye toh? Opo ora ingat mati?” seorang bapak
berseru. Pak Trisno namanya.
“Kayak kagak tau aje Pak.. Pak.. Itu udeh jadi kebiasaan pak. Loh kalau gak korupsi dikatain
belum punye jabatan tinggi. Udeh jadi budaye pak Tris. Boro-boro
inget mati.” Pak Enal menimpali.
“Coba
ya uang itu dikasih ke mbok. Warung
pasti mbok dibenerin. Besar-besar sampai ke ujung gang masjid sana.” Mbok Inem
pemilik warung ikut berkomentar.
“Iyalah
Mbok, Pak. Mending jadi tukang becak seperti saya. Ndak pernah korupsi, hahaha,” sambung Mang Imam.
Yan
tersenyum mendengar curahan hati insan-insan bawah. Pak Trisno, mbok Inem, Pak Enal,
Mang Imam, dan insan-insan lain adalah lambang diskriminasi kota itu. Kehidupan
timpang yang mereka jalani berbanding terbalik dengan jalan cerita hidup bapak
tua sang koruptor di televisi itu. Peluh dan keringat yang selalu keluar dari
daging Mang Imam, uang parkir yang tak sepadan dengan pengeluaran keluarga Pak
Trisno, penghasilan pas-pasan Mbok Inem sebagai pemilik warung kopi, dan masih
banyak insan-insan lain yang dicederai ketidakadilan. Lihat mereka yang berjas
dan bekerja di dalam ruang berpendingin itu! Uang hasil kerja otot-otot para
insan hanya dipakai untuk bersenang-senang. Hingga akhirnya, merekalah yang
mati. Mati ditangan hukum. Dirajam di dalam jeruji besi, meski tak sampai
kehilangan nyawa. Para insan piye? Masih saja berkutat dengan
kehidupan mereka yang jujur. Ndak
pernah korupsi.
Beranjak
dari kursi, Yan berlalu dengan secercah harapan. Diengkolnya kick starter motor tua itu. Dekdekdekdekdek.... Asap abu-abu itu keluar
bersamaan dengan suara bak mesin ketek
menderu-deru.
30
menit hilang berbaur dengan kemacetan kota. Stang motor pelan-pelan berbelok
masuk ke sebuah gerbang gedung putih. Yan berhenti tepat ditengah-tengah gerbang.
Dipandanginya dalam-dalam gedung itu. Seringai dimulutnya mencuat. Menguatkan
diri sendiri. Hari itu adalah pengumuman wawancara. Siapa yang lulus, muluslah
jalannya untuk bekerja.
Sama
seperti saat wawancara, beberapa sarjana muda tengah berdiri di depan papan
pengumuman. Bersenggol-senggolan dan mata sibuk melototi kertas bertabel. Ada
yang berbalik badan seraya memaki-maki. Ada yang mengempalkan tangan sambil
berteriak yes. Macam anak sekolahan
yang baru menerima raport. Ribut.
Beberapa kali satpam menegur ulah mereka. Yan mendekati kerumunan sepuluhan
sarjana itu. Matanya yang dipicingkan, memfokus ke satu titik. Ironi. Tak ada
namanya di deretan kertas pertama. Diulanginya lagi. Nihil. Masih tersisa dua
kertas lagi. Lehernya mendadak keras. Tubuhnya menjadi ringkih. Di dua kertas
tersisa tak ada nama Yan. Janita Dwi Putra tak tercantum di tabel itu. Singkat
kata, gagal.
Yan
kembali terduduk di kursi besi itu. Merenung. Pandangannya memang terhalangi
keramik-keramik, tapi pikirannya jauh menembus tanah. Terus-menerus hingga
bayangan gelap yang dia temui.
“Selamat
saudara Ian. Selamat.” Yan mengenali suara perempuan itu. Ya. Ibu pewawancara.
Yan tersadar dari lamunannya. “Selamat? Apa yang pantas diselamati?” Yan
mengguman.
“Selamat?
Saya tidak berhasil Bu. Apa yang pantas untuk itu?” Suara Yan sedikit mengeras.
“Ini
kegagalan ke berapa, Ian?” Nada Ibu pewawancara dibuat selembut mungkin.
“Dua.”
“Haa!
Baru dua? Baru dua tapi Anda sudah seperti orang gila. Baru dua! Orang diluar
itu sudah ratusan kali gagal. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Menyerah?
Bunuh diri? Tidak! Semua orang sudah diberikan jatah gagal. Dan jatah gagal
Anda belum Anda habiskan.” Sambil menyeringai, nada bicara Ibu pewawancara
meninggi. Yan tersentak. Apa yang baru saja ibu pewawancara katakan adalah
benar.
“Maksud
dari selamat tadi apa, Bu?”
“Anda
memang tidak berada di barisan nama itu. Anda tahu kenapa?”
“Tidak
Bu.” Jawab Yan pendek. Tegas. Itulah yang membuat Ibu pewawancara menilai Yan
berbeda.
“Selamat,
Anda kami tempatkan di universitas di Malaysia.”
“H.a.a.a?
A..p..a?” Yan tergugu. Tangannya mengeras memegang amplop yang diberikan Ibu
pewawancara.
Pikiran Yan masih dipenuhi tanda tanya. Mulutnya hanya terbuka
setiga jari. Pelan-pelan dibukanya amplop putih yang bercap logo universitas.
Terpampang jelas namanya di isi surat.
“Setelah
disetujui direksi kantor, Anda kami sekolahkan di Malaysia. Sepulangnya dari
sana, pekerjaan menunggu Anda.” Jelas Ibu pewawancara seraya tersenyum.
Senyuman yang membuka kisah baru Yan. Yan tak pernah menyangka akan seperti itu.
Jelas
sudah sekarang. Bukan jelas. Tapi sedikit tahu akan kelanjutannya, masa depan. Menyingkap
secercah tabir, penutup sebagian penglihatan. Penglihatan Yan. Menerka-nerka
takdir hidup. Menggantungkan sebait-demi-bait cita. Hingga telah merasa menemui
jalannya. Yan berteriak “aku berhasil.” Persis dengan apa yang hendak ia teriak.
Seringai mulutnya nampak tatkala tahu nasibnya berkebalikan dengan Sarjana Muda. Hari itu, kota telah
berbaik hati. Diskriminasi kotak-kotak megah tak menyapu nasib Yan. Serasa
kotak-kotak sukar mengalahkan titik terang dari kehidupan yang jujur.
Kesuciannya telah melanggar kesewenang-wenangan kota. Jauh dari gigi-gigi tikus
yang berjalan mencari jiwa yang ditindas. Melangkah kembali seraya menundukkan
kepala ke arah Yan.
Tentang
uang? Tentang ketidakadilan? Kala ini Yan terhindar.
Kemelaratan
masih menghantui jiwa-jiwa insan. Tapi setidaknya, ada satu insan yang
tersenyum malam nanti. Cukup untuk mewakili kesenangan insan-insan yang lain.
Malam nanti, ada yang berharap bahwa jiwa keinsanannya masih membumbung tinggi
tatkala dia pulang.
HABIS...
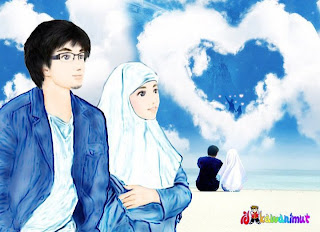
.jpg)
Komentar
Posting Komentar
There's Any Comment Guys?