Mozaik
/ Keraguan dan Fragmen Hidup yang Akan Hilang
Aku tepat berada didepan gerbang kampus. Apa benar sekarang aku kuliah? Aku gali
ingatan, muncul siluet-siluet. Aku melihat bayangan hitam, bayangan tubuhku
yang berlarian, dengan tubuh terbalut kemeja licin dan jeans, serta sepatu ket
khas anak kuliahan. Seraya meneguk liur aku sadar, suatu fragmen hidup yang aku
cita-citakan akan hilang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Setelah aku masuk
ke lobi, bertemu teman-teman baru di kelas baru, dengan seragam baru, dan kukira,
aku tak kan menemukan hal baru. Akankah aku kembali menjalani rutinitas seperti
yang telah aku rasakan duabelas tahun ini? Pangkat dibahu berbisik, lupakanlah Kawan. Dasi mengiang, aku akan bersamamu, Kawan. Siluet itu
pudar memencar, berubah. Siluet itu kini menjadi berwarna, sewarna dengan
seragamku : biru muda. Langkahku
pasti, wajahku tegak berdiri, senyumku berseri, dan kurangkul seorang teman
baru yang berdiri disampingku sedari tadi. Aku sadar, suatu jejak-jejak hidup
yang kuinginkan sulit tercapai, bahkan fragmen hidup itu akan hilang. Sampai
tiba suatu keadaan yang aku benarkan.
// Kemeja Licin dan Nyonya Eksekutif
Sepertinya untuk empat tahun kedepan, baju-baju
mewahku yang terlipat di rak los kontrakan
hanya akan itu-itu saja. Toh, ku merantau ke tanah sultan, dengan menikmati
hamparan ubi kayu sejauh mata memanjang di pertengahan Lampung, dengan
berbosan-bosan di mushola kapal Manggala sejam-an lebih di selat Sunda, dengan
dingin dan laparnya perut di jalur Pantura, dengan keletihan dan rasa lega di
pelataran shelter bis Jombor tidak untuk plesiran
dengan baju-baju mewah. Mewah, aku masih mengacu ke definisi lain : kemeja. Bercelana
jeans dan kemeja licin dengan kancing dikerah telah menunjukkan kemewahan. Maklum,
aku hanya memakai kemeja satu-satunya yang aku miliki saat-saat penting saja.
Kalau tidak dies natalis himpunan
mahasiswa, ya pertunjukkan band
kampus. Tidak seperti dengan jejeran kampus di jalan Babarsari. Saat mereka hari
ini memakai kemeja licin dengan jeans bermerk, besoknya memakai jaket tebal dan
elegan dengan celana berbahan terbaik, besoknya lagi entah apa namanya, aku
hanya setia dengan sebuah seragam kebesaran : biru muda atasnya dengan hitam
dibawah, ditambah sentuhan pangkat beraksen kuning serta dasi biru tua. Dua hal
terakhir adalah sebuah penyelamatan bagiku, juga bagi mahasiswa kampusku.
Dengan dua hal tersebut, kami terhindar dari kesalahpahaman bahwa kami adalah
sopir taksi, dan kesalahpenyangkaan bahwa kami pegawai minimarket.
Kuceritakan sebuah kekononan. Lima tahun sebelum aku
kuliah, seragam kampusku benar-benar mirip sopir taksi yang sering nongkrong di tepian jalan Babarsari.
Tanpa dasi, tak berpangkat, tak ada badge
dikantong, serta kancing baju yang terbuka sampai terlihat ke tengah dada.
Banyak mahasiswa yang mengadu ke petinggi kampus perihal hal absurd yang dirasakan sebagai suatu
penjatuhan harga diri. Mereka merasa menjadi sekumpulan orang berkasta ksatria
yang berseragam orang-orang sudra. Mereka berpikir mereka adalah zat
radioaktif, yang semestinya disimpan baik di drum-drum berlapis beton zat
khusus, bukan hanya dibuang dikantong kresek lalu dilempar ke kali Code. Bukan
merendahkan para sopir yang berseragam, tapi hendaknya petinggi kampus tahu
arti dari kesamaan seragam itu.
Mahasiswa protes, bersungut ingin meng-upgrade seragam. Hingga terjadi satu hal
yang memicu terwujudnya gelombang protes mahasiswa : kehilangan motor di
parkiran kampus. Menurut keterangan saksi, ada seseorang yang menyamar menjadi
mahasiswa dengan menggunakan seragam kampus. Satpam tak ambil pusing, karena
dia tahu mahasiswa sering berkeliaran hingga larut malam di area gedung. Karena
tragedi itu, petinggi kampus bersidang. Sidang penting yang ditunggu mahasiswa
menghasilkan suatu deklarasi. “Pakaikan dasi!” Itulah isi deklarasi. Seminggu,
sebulan, setengah semester, rupanya mahasiswa cukup puas. Setidaknya ada
sedikit peningkatan seragam kasta. Yang dulu berseragam orang-orang sudra,
sekarang memakai seragam waisya.
Dan pangkat itu berasal dari mana?
Rupanya ada salah satu pegawai rendahan di kampus
yang berpikir maju dibanding para petinggi kampus. Dia tetap melihat ada
praktek sopirisasi dikalangan mahasiswa-mahasiswa meskipun dasi telah mengikat
kuat dileher. Perlu ada sentuhan terakhir untuk suatu perubahan besar. Satu
logo untuk mahasiswa baru, dua logo untuk mahasiswa tingkat dua, tiga logo
untuk mahasiswa tahun ketiga, dan empat logo untuk mahasiswa sulung.
Benar-benar jenius. Usul pengadaan pangkat itu maju ke sidang, sama seperti
saat sidang pendeklarasian dasi. Pegawai rendahan dengan usulan jenius
dihadapkan kepada para petinggi kampus, persis seperti mahasiswa sulung
bersidang mempertahankan argumen di tugas akhir. Warna latar hitam, dengan
jumlah logo sesuai tingkat kuliah, logo-logo dan tulisan berwarna kuning emas.
Pegawai itu duduk perlahan, gamang setelah mempresentasikan usulan perubahan.
Terdengar lamat-lamat tepukan dari penghadir sidang, terus hingga pegawai
tersenyum. “Usulan diterima dan Anda diangkat menjadi pegawai negeri,” kata
ketua kampus. “Terima kasih, pak pegawai rendahan yang sekarang jadi pegawai
negeri,” ujar mahasiswa haru biru.
Aku berhipotesa tentang seragamku : tidak seburuk yang mereka pikirkan jika
tidak berdasi dan tak berpangkat. Aku mengetesnya. Aku bercermin di toilet
kampus. Apa benar jika dasi ditandaskan
dan pangkat dilepas, aku akan seperti sopir taksi jalan Babarsari atau pegawai
minimarket di jalan Adi Sucipto? Benakku bertanya. Aku lepas atribut
seragam, dan sepuluh detik setelah itu, aku terburu-buru kembali memakai
semuanya. Memang, pernyataan itu benar dan hipotesaku terbantahkan.
Untuk beberapa alasan, terlebih karena aku adalah
karakter pemilih yang sulit, berseragam adalah satu-satunya pemecahan masalah
dalam problem busanaku. Memilih busana adalah suatu permasalahan besar bagiku,
dan jika ada yang bertanya mengapa, akan kujawab dengan menunjukkan lengan dan
tanganku yang kecil. Pernah sekali aku mendengar perkataan seorang desainer
ternama Indonesia di suatu infotainment.
Jika berbadan kurus, pakailah busana
berwarna putih, itulah kurang lebihnya. Warna? Ah, tak lebih dari suatu
gelombang elektromagnetik. Sejauh mana kemampuan warna dapat menghipnotis manusia
bahwa objek yang mengenakan busana berwarna putih adalah orang gemuk? Aku tak
mengerti, dan permasalahanku untuk busana tidak terselesaikan. Hingga munculah
kampusku, dan munculah seragamku. Karena berseragam, aku tak perlu pusing
memilih busana yang harus kupakai.
Singkat. Cukup sudah. Problem solved. Namun, muncul masalah lain. Ironis. Meski telah
memakai seragam lengkap dengan atribut, seorang pengunjung minimarket masih
memanggilku seolah aku adalah karyawan. Pada saat itu aku berputar-putar di
jejeran rak roti kering, dan ibu macam eksekutif muda itu memanggilku dengan kalimat,
Pak, bisa tolong panggilkan managernya?
Penyataan sederhana itu mengandung tiga maksud sekaligus : bertanya,
memerintah, dan penghinaan. Aku tak pernah menyangka jika kata ganti pak telah bisa disematkan padaku yang
masih berusia delapan belas tahun. Itu bisa ditoleransi. Nah, jika dia masih
mengira bahwa seragam kebanggaanku adalah seragam pegawai minimarket, itu
adalah wujud penghinaan kepadaku, juga pada dasi dan pangkatku, bahkan
kampusku. Seragamku lebih dari lambang almamater, seragamku adalah pengejewantahan
masa laluku sebagai mahasiswa berseragam jika akan dikenang nantinya. Dan
seakan semua berguguran saat ibu muda itu datang kepadaku. Aku ini mahasiswa berseragam, Nyonya! Ternyata, seragam saja tidak
cukup.
/// Perkenalan, Cinta, dan Sok Lecturer
Pernah bersenggolan bahu dengan seseorang tak
dikenal yang nyatanya selalu duduk tepat dibelakang kalian tiap kali kuliah
kalkulus? Atau dengan mahasiswa tak dikenal yang nyatanya selalu se-ruang saat
ujian fisika lima semester berturut-turut? Maklum saja itu terjadi. Mahasiswa,
dalam jumlah besar muncul seperti hijrahnya Hummingbird berleher rubi yang
terbang ratusan kilometer menuju Amerika Pusat, terus tanpa henti ke Amerika
Utara melintasi teluk Meksiko. Sayangnya, pertambahan mahasiswa tersumbat
disatu titik : lulus. Ada kontradiksi besar layaknya sinar matahari menembus
lapisan udara tatkala hujan mengguyur Sahara. Dalam perspektif penambang emas
amatiran, fenomena kelulusan mahasiswa layaknya sekarung pasir yang jika
disaring hanya menghasilkan segenggam biji emas murni. Ya, mahasiswa yang lulus
bak penduduk kampung Rantau yang datang berombongan dan keluar satu-satu sambil
menggenggam amplop bantuan pemerintah. Keadaan kampus seperti pipa air
berpenampang besar diawalnya namun terus menirus, kecepatannya aliran cenderung
melambat, tak memenuhi hukum Bernoulli. Imbasnya, mahasiswa yang saling
bersenggolan bahu tadi tak saling kenal, saking banyaknya mahasiswa
berkeliaran. Semuanya menumpuk. Jangankan dengan kakak atau adik tingkat, dengan
teman seangkatanpun agak sangsi jika ingin dikatakan saling mengenal.
Tapi untuk kampus yang berseragam, terkhusus
kampusku, itu berbeda. Tanyakan saja pada anak semester tiga tentang keberadaan
anak semester tujuh yang berlainan prodi. Mereka pasti akan menjawab lugas,
tepat, atau bahkan akan diantarkan tepat ke depan wajah anak semester tujuh
yang dituju. Heran, terkadang aku berpikir ada semacam sistem perkenalan tak langsung
yang efektif antaranak-anak kampusku. Mungkin ini adalah efek dari penglihatan
yang itu-itu saja. Kami hanya
bergulat pada sepetak tanah, mungkin hanya berukuran tiga puluh kali lima puluh
meter. Kami layaknya dihubungkan melalui petak-petak ubin di koridor, menembus
dinding-dinding kelas dan laboratorium, menjejak lapangan basket dan aspal
parkiran, berbelok, dan berkumpul di kantin kampus atau serambi masjid. Kami
disatukan oleh nasi goreng berminyak dan kopi berkrim panas yang mengepul
asapnya. Atau, karena berkumpulnya anak-anak kampus di serambi masjid demi
menghadiri rapat-rapat kecil panitia dies
natalis dan bakti sosial. Semua itu membuat diantara kami timbul
perkenalan, lalu muncul perhatian, dan akhirnya hadirlah cinta. Aku meneliti
semua itu, ternyata tak jauh berbeda dengan fenomena sebelum aku kuliah. Aku mengingat
sesuatu, saat wali kelas ikut campur dalam pesona-pesona cinta remaja, ternyata
ada dosen yang ikut tangan juga. Kuceritakan tentang seorang dosen yang
kuanggap menarik dan mungkin tak terjadi dikampus lain. Kulabeli beliau sebagai
sok lecturer. Beliau selalu membaur (sok)
akrab dengan mahasiswa, entah mahasiswa sedang berkutat dengan laptop, atau
sedang menggarisi tepi-tepi kertas laporan, atau tengah membaca koran di
dinding kaca, atau bahkan tengah menyuap nasi goreng berminyak. Aku tahu ini
adalah sebuah dosa jika membicarakan orang lain, tapi beliau senang dengan itu
semua (senang melakukan hal-hal yang sok). Ada dua hal khas yang sering beliau lakukan
jika ada mahasiswa tingkat pertama (cewek) sedang duduk-duduk didekatnya dan mahasiswa
semester tujuh (cowok) lewat melintasi mereka.
Hal pertama.... Sang dosen berinisiatif dan memulai
ke-sok-annya dengan memanggil mahasiswa semester tujuh yang tengah melintas.
“Hey, hey,” panggil si dosen. Mahasiswa semester tujuh menoleh. Dan inilah
pertanyaan khasnya, “kamu, kamu kenal gak sama dia?” tanpa basa-basi langsung
bertanya dengan pertanyaan absurd.
Suatu pertanyaan yang sangat amat tidak penting, lebih-lebih bagi mahasiswa
tingkat tujuh yang sedang mabuk kecubung digoyang tugas akhir. Si mahasiswa
tingkat pertama langsung bingung karena tangan si dosen menunjuk-nunjuk
tubuhnya. “Gak, Pak, gak kenal,” balas mahasiswa semester tujuh polos, serta
jengkel. “Nah kalau belum kenal, kenalan dulu, ayo kenalan dulu,” perintah si
dosen. Demi menjaga mood si dosen,
kedua mahasiswa akhirnya berjabat tangan kaku, kikuk, saling berbalas senyum
masam, seraya bergumam dalam hati masing-masing, apa-apaan nih dosen. Satu hal yang positif, karena ke-sok-an si
dosen, kami semua saling mengenal, tak terlewat satu nama pun.
Hal kedua adalah, beliau selalu bertanya sok akrab
perihal keadaan hubungan perpacaran mahasiswa di kampus. Seakan-akan beliau
bisa menyelesaikan perkara putus, atau bisa merajut kembali hubungan yang
kandas. Atau bagi yang menjawab lagi jomblo
pak, beliau seolah-olah bisa mencarikan jodoh yang pas dan pantas. Aku
berpikir, itulah trademark kampusku.
Dari fenomena itu, aku menarik suatu kesimpulan. Aku sekarang berada
dilingkungan yang erat, yang saling peduli satu sama lain, yang saling
memperhatikan, yang saling memahami, dan yang terpenting, keluargaku bukan
hanya satu kelas, bukan hanya satu prodi, tapi keluargaku adalah satu kampus.
Karena keseragaman, kami saling mengenal satu sama lain, melewati batas-batas
prodi, melebihi kotak-kotak jurusan. Selepas lulus, akan ada jejak yang
tertinggal, yaitu nama-nama. Dan dalam ruang lingkup kecil nan keseragaman, aku
menemukan keluarga besar. Perkenalan, cinta, dan sok lecturer adalah jalinan kuat, bukti kecil bahwa kami bukan
sekedar anak kampus yang berseragam. Ini
kuliah atau SMA? Atau SMP?
///Menemukan
yang Sesungguhnya
Suatu hal yang dimulai akan berakhir disuatu ujung.
Semua makhluk, entah bernyawa atau mati, mengalami suatu proses perubahan, dan
pada satu waktu semua akan kembali ke peraduannya, ke penciptanya. Di sebuah
ujung, dunia berkilau menjadi titik yang mengambang. Mungkin akan kembali
seperti bermiliar-miliar tahun yang lalu. Gumpalan kecil, berputar, berspiral,
berenergi tinggi, terus tinggi, dan meledak. Maka suatu waktu jagad yang luas
ini akan menciut, menjadi sebuah titik lagi. Menciut dengan energi rendah,
terus rendah, berspiral, berputar, dan menjadi gumpalan kecil, akhirnya titik
kecil. Dan seluruh elemen di jagad ini akan mengalami proses yang berbeda-beda,
tapi tujuan akhir tetap sama : menjadi titik. Kami adalah bagian dari elemen
tersebut. Kukisahkan suatu pelajaran yang membuatku berpikir bahwa kami akan
tetap sama dengan kampus lain, walau dalam prosesnya, kami berbeda.
Kampusku, lebih dari sekedar ikatan perkuliahan.
Memang benar hukum Coulomb, gaya tarik-menarik antara dua muatan akan semakin
besar jika jarak keduanya semakin kecil. Kampusku layaknya kumpulan-kumpulan
medan listrik abadi, dengan kami sebagai muatan-muatannya. Titik-titik terkuat
medan listrik, tentu, di dalam kelas. Kami adalah muatan fleksibel, disuatu
keadaan kami bermuatan positif, dan disaat lain bisa berganti menjadi negatif.
Aku berlaku positif bagi temanku yang negatif, dan aku akan bernegatif pada
teman yang bermuatan positif. Itu berlaku ke semua muatan, ke kami. Efek
tersebut membuat kami saling tarik-menarik dan tak ada peristiwa tolak-menolak.
Dan ada, hukum dua termodinamika meluruskan segalanya.
Aku siapkan Jangkrikku, si sepeda dortrap. Hari ini
adalah hari Kamis, harinya termodinamika. Kutempelkan daun kuping ke pintu, dan
benar saja, suara menggema sedang menjelaskan tentang termodinamika. Aku
terlambat. Aku mundur beberapa langkah, mempersiapkan lagu yang harus aku
bawakan. Ya, hukuman bagi mahasiswa yang terlambat adalah menyanyi, seraya
dipermalukan. Hukuman yang benar-benar tidak berjiwa mahasiswa. Teringat kala
aku terlambat lima belas menit ketika duduk di kelas dua SMA, aku mendapat
hukuman yang lebih berkelas : ceramah
singkat. Namun setiba aku di kelas termodinamika, menyanyi adalah pilihan si
dosen. Cukup efektif. Cukup efektif untuk membuat anak-anak kelas terlambat
berombongan. Aku selalu tertawa terbahak-bahak tatkala ada teman yang suaranya
sumbang menyanyi lagu daerah asalnya. Bahasa aneh yang pertama kali aku dengar
ditambah lekukan-lekukan gelombang suaranya yang entah tingginya berapa oktaf
membuatku menangis tertawa. Dan lima menit yang akan datang, aku yang bakal menjadi objek tertawaan.
Cekrekk... Tanpa dikomando, anak-anak kelas langsung
bersuitan tatkala sebagian tubuhku masuk ke ruang kelas. Dosen langsung mempersilahkanku
masuk dan kemudian menyingkir ke belakang kelas. Panggung pertunjukanku pagi
ini telah siap. Aku menghela nafas panjang dan lambat-lambat menghembusnya.
Sepertinya aku akan membawa lagu daerah bertemakan cinta. Laguku berceritakan
tentang dua anak manusia kampung yang sedang kasmaran, sedari kecil bersama,
dan tak sadar bahwa umur mereka telah beranjak dewasa. Tiap hari selalu berdua,
sampai-sampai orang dikampung tahu perihal hubungan mereka. Dibagian reff, aku menaikkan nada, lirik-liriknya
bercerita bahwa si pria benar-benar mencintai si wanita dan hendak meminangnya.
Jangan kira aku bernyanyi dengan suara macam Bon Jovi, suaraku tak lebih dari
suara orang berteriak yang tengah tersesat dibelantara sungai Kuning. Nada
suaraku kemana-mana, sampai-sampai aku tak lagi mendengar tawa anak-anak kelas
karena sibuk mencari nada-nadaku yang berserakan hilang. Aku tiba dibagian
ujung, kulantunkan reff terakhir guna
menyelesaikan pertunjukan absurd Kamis
pagi. Bait meresmike kitek bedue aku
rendahkan ujungnya, dan dengan sedikit hentakan kaki, pertunjukan solo
berakhir. Aku merasa seragam biru mudaku terlucuti dan berganti dengan seragam
putih merah. Aku kembali ke dunia les sore, dan ini datang dari dosen yang
tersenyum di belakang kelas. Aku bergegas dengan wajah merah.
Ada satu hal yang membuat aku menyukai cara si dosen
mengajar. Beliau kadangkala menganalogikan materi kuliah dengan kehidupan
sehari-hari. Semisal kami menemukan kesulitan dalam mendefinisikan pengertian
entropi. Perbandingan yang sangat cocok adalah kehidupan merantau, katanya,
seperti yang banyak kami rasakan. Disaat pertama merantau, jauh dari orangtua,
mengurusi makanan sendiri, menyikat kerah-kerah baju sendiri, entropi kehidupan
kami berubah. Butuh waktu untuk membuat entropi menjadi seimbang. Lama
kelamaan, kehidupan merantau yang baru akan kami rasakan tanpa beban, dan
disaat itulah keadaan kembali menjadi seimbang. Juga, kehidupan saat semester
satu memiliki perbedaan entropi dengan keadaan semester akhir. Begitu banyak
tekanan akan bermunculan. Dan entropi akan berubah secara signifikan jika kami
tak dapat menyeimbangkan keadaan. Cukup efektif untuk menerjemahkan kata-kata
yang sangat fisikais.
Pikiranku kerap melanglang buana memikirkan ceramah
ilmiah beliau meski beliau telah membuka lembar materi baru. Ingatanku masih
membekas saat beliau berkata bahwa entropi sistem saat berubah dari satu
keadaan ke keadaan lain tidak bergantung pada proses. Dalam kata lain,
perubahan sistem dilihat dari dua keadaan, keadaan awal dan akhir. Konsep
inilah yang membuat aku berpikir tentang kesamaan kami dengan kampus lain. Aku
berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa langkahku ini sudah merupakan garis
takdir, dan fragmen hidup yang aku impikan akan menyata hilang adalah titik
awal. Kemudian, aku melangkah ke dalam kampus. Sejatinya aku tak bisa
mengatakan bahwa kehidupan kampusku berbeda, karena sekalipun aku belum pernah
merasakan atmosfer kehidupan kampus lain. Namun, aku dan teman-temanku akan
sepakat jika ada suatu anomali proses. Aku pernah bertanya ke seorang teman,
perihal apakah dia menemukan keadaan baru di kampus. Jawaban yang kudapat
adalah, sepertinya aku kembali ke masa
sekolah, hanya saja aku sekarang seorang mahasiswa, bukan siswa. Malah dia
kembali bertanya kepadaku, apakah kau tak
bosan memakai seragam ini? Kubalas, ini
adalah suatu keuntungan bagiku, kawan. Semua itu adalah serpihan proses
kehidupan kampusku. Dan tahukah jika ada suatu keadaan yang menyamakan kami
dengan kampus lain? Mau seberapa derajat perbedaan, mau seberapa jauh jarak
memisah, mau seberapa tinggi tembok menghalang, kami tetap mahasiswa. Tetap
mahasiswa! Apa yang dituntut kepada pundak mahasiswa selepas tali toga
digerakkan? Tidak lain adalah kerja. Itulah akhir dari proses ini, titik dimana
kami adalah mahasiswa biasa, mahasiswa yang sama dengan kebanyakan.
Aku melamun jauh menembus tembok, pergi melupakan
dosen yang sekarang tengah berada tepat didepanku.
“Mas, bisa ulangi bunyi teorema Carnot?” Beliau
menodongku. Aku terkesiap. Makhluk apa
pula teorema Carnot itu? Syaraf sensorisku cepat menghantarkan impuls dari
otak ke mulut dan lidah. “Saya tidak kenal pak, sungguh pak!”

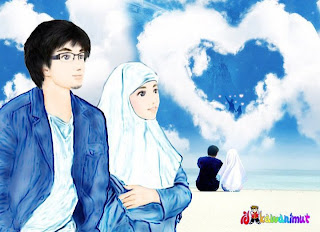
.jpg)
boleh dak coh kamu kuliah sambil ngamben anak? aman boleh, lemak nga cuti bini dulu tegal. aga sedih asek ku.
BalasHapus